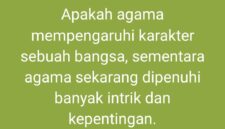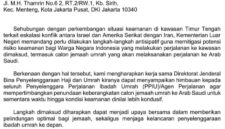CIANJUR – Malam Selasa Kliwon, 12 Januari 2026, Gunung Padang tidak sekadar basah oleh hujan. Ia seperti sedang menunggu. Sejak pagi hingga sore, air turun tanpa henti, membungkus situs megalitikum itu dalam kabut dan sunyi. Namun menjelang pukul 19.40 WIB—saat rombongan tiba di kaki gunung—hujan berhenti mendadak. Tidak perlahan. Tidak menyisakan gerimis. Seolah ada isyarat yang tak terucap.
Misa Ekaristi Awal Tahun digelar di Teras 5, titik tertinggi Gunung Padang, tempat yang oleh para penjaga situs dipercaya menyimpan jejak peradaban tua dan lapisan-lapisan kesadaran yang telah lama diam. Misa dipimpin Romo Yos Bintoro, Wakil Uskup untuk umat Katolik di lingkungan TNI–Polri. Doa malam itu dipanjatkan bukan hanya untuk membuka tahun baru, tetapi juga sebagai pengakuan sunyi atas dosa manusia terhadap gunung, air, dan bumi—terhadap alam yang terlalu lama diperlakukan sebagai benda, bukan kehidupan.
Sebelum menapaki 378 anak tangga utama, rombongan menjalani ritual penyucian: membasuh tangan, wajah, dan kepala, lalu meneguk air dari mata air Gunung Padang. Ritual dipandu Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana, bersama juru pelihara Atma. Air itu dingin, bening, dan diminum dalam diam—seolah menjadi penanda bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik.
Sejak langkah pertama, suasana berubah. Di antara bebatuan tua dan pohon yang berdiri tanpa suara, beberapa peserta mencium wangi bunga. Harum lembut, tidak menyengat, namun jelas terasa. Tidak ada bunga di sekitar. Tidak ada sesaji. Wangi itu datang, pergi, lalu kembali, seperti napas yang tidak ingin dilihat.
Di teras pertama, ketika doa pembuka dilantunkan, percikan air mengenai beberapa peserta. Bukan hujan. Langit tetap mendung, tetapi kering. Tidak ada daun basah di atas kepala. Percikan itu singkat, dingin, dan nyata. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang bersuara. Malam seolah meminta semua orang untuk menyimpan pengalamannya sendiri.
Puncak keheningan terjadi di Teras 5 saat konsekrasi Ekaristi. Awan tebal yang sejak sore menutup langit tiba-tiba terbelah. Bukan memudar, tetapi membuka—menciptakan celah besar seperti lubang cahaya. Langit berubah biru gelap, nyaris hitam, dan bintang-bintang muncul sangat terang. Beberapa rasi terlihat jelas. Planet Venus tampak besar dan mencolok, berdiri sendiri di langit malam, seolah diletakkan tepat di atas altar batu.
“Ini bukan malam biasa,” ujar Romo Yos pelan usai misa. “Kami berdoa di tempat yang hidup. Doa Nusantara. Doa pertobatan manusia kepada ciptaan Tuhan.”
Nanang Sukmana menyebut, dua malam sebelumnya hujan turun sangat deras tanpa jeda. “Saya ragu kegiatan ini bisa terjadi. Tapi malam Selasa Kliwon ini berbeda. Saat doa dimulai, langit terbuka. Dalam pemahaman kami, Selasa Kliwon adalah malam cahaya. Padang berarti terang. Malam ini, makna itu seakan menjelma,” katanya.
Brigjen TNI (Mar) F.J.H. Pardosi mengaku merasakan ketenangan yang tidak biasa. “Ada rasa dilepaskan. Seperti sesuatu yang berat ditanggalkan tanpa diminta,” ujarnya singkat.
Usai misa, awan kembali menutup langit. Cahaya bintang menghilang. Saat rombongan menuruni tangga dan tiba di kaki gunung, hujan turun lagi—deras, singkat, lalu berhenti. Seperti penutup yang disengaja.
Gunung Padang kembali diam. Batu-batu purbanya berdiri tanpa saksi, menyimpan wangi yang tak terlihat, percikan yang tak diketahui asalnya, dan langit yang sempat terbuka. Malam Selasa Kliwon berlalu, meninggalkan satu kesan yang sama pada semua yang hadir:
di tempat tertentu, alam tidak hanya menjadi latar, tetapi ikut berbicara—dengan caranya sendiri.
PWGK Gunung Kaler Gelar Baksos Ramadan, Bantu Lansia Tunanetra di Sidoko PASTI Soroti SP3 Kasus Dugaan Diskriminasi Siswi SD di Sorong, Minta Atensi Presiden dan Kapolri Presiden Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro, Tegaskan Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Percikan Las Diduga Picu Kebakaran Pabrik Kosong di Kamal Muara Penjaringan Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Besok, Fokus 9 Pelanggaran