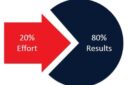Oleh: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.
Kematian media tidak selalu ditandai oleh pengumuman tutup redaksi atau berhentinya mesin cetak. Dalam banyak kasus, media justru mati secara perlahan—senyap, tanpa seremoni, dan sering kali tanpa disadari publik. Para pengkaji media, seperti McChesney (2004) dan Curran (2011), telah lama mengingatkan bahwa krisis pers tidak hanya soal bisnis, tetapi juga soal runtuhnya fungsi sosial media dalam demokrasi.
Selama ini, krisis media kerap dibaca melalui penutupan institusi pers atau death by closure (kematian karena tutup). Kita menyaksikannya pada banyak media cetak di Indonesia dan dunia. Bentuk kematian ini paling mudah dikenali dan sering dijadikan indikator utama krisis industri pers, seperti yang ditulis Picard (2010) dalam ekonomi media. Namun, fokus berlebihan pada penutupan media justru menutupi bentuk-bentuk kematian lain yang lebih sunyi tetapi berdampak luas.
Bentuk kedua adalah death by silence (kematian karena diam). Media masih ada secara administratif—punya nama, domain, bahkan badan hukum—tetapi nyaris tidak lagi memproduksi jurnalisme yang bermakna. Di Indonesia, fenomena ini jamak terjadi pada media daring lokal atau media yang muncul saat momentum politik, lalu menghilang setelah kepentingan usai. Dalam konteks global, kondisi ini sejalan dengan fenomena news deserts (Abernathy, 2018), wilayah yang secara formal memiliki media tetapi secara praktis kehilangan liputan publik yang berkualitas.
Bentuk ketiga adalah death by hollowing (kematian karena pengosongan). Media tetap hidup dan aktif, tetapi kapasitas jurnalistiknya terkikis dari dalam. Redaksi menyusut, liputan mendalam menghilang, dan berita cepat berbasis “klik” mendominasi ruang redaksi. Sejumlah kajian menyebut fase ini sebagai era post-industrial journalism, ketika tekanan ekonomi dan logika platform digital mengubah jurnalisme menjadi komoditas instan (Anderson, Bell, & Shirky, 2012). Media tidak mati sebagai organisasi, tetapi mati sebagai institusi pengawas kekuasaan.
Yang paling problematik adalah tipe kematian zombie media (media zombie). Media tampak hidup dan produktif, tetapi secara substantif tidak lagi melayani kepentingan publik. Konten dipenuhi advertorial terselubung, kepentingan politik, atau agenda ekonomi tertentu. Dalam kajian global, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena media capture dan paralelisme politik, ketika media berada dalam cengkeraman kekuasaan dan modal (Hallin & Mancini, 2004; Schiffrin, 2017). Dalam konteks Indonesia, media zombie kerap menguat dalam siklus elektoral dan dalam struktur kepemilikan media yang terkonsentrasi.
Tiga bentuk terakhir—death by silence, death by hollowing, dan zombie media—membentuk apa yang dapat disebut sebagai dark number of media death (angka gelap kematian media). Konsep ini meminjam logika dark figure of crime dalam kriminologi, yakni realitas yang tidak tercatat dalam statistik resmi tetapi berdampak nyata dalam kehidupan sosial.
Kalau kita membaca krisis media di Indonesia, ancamannya tak lagi sekadar penutupan redaksi. Banyak media lokal justru mengalami kematian pelan-pelan: death by silence (diam yang berkepanjangan), hollowing (pengosongan fungsi jurnalistik), atau menjelma menjadi zombie media yang kehilangan peran pengawasan dan penguatan demokrasi.
Dalam forum Kaleidoskop Media Massa 2025 pekan kemarin, PWI Pusat menegaskan bahwa mungkin diperlukan dukungan pemerintah, tetapi harus adil, terukur, dan tidak menggerus independensi redaksi. Tanpa langkah itu, media mungkin tetap hidup di atas kertas, namun perlahan mati dalam fungsinya sebagai penyangga demokrasi.
*) Penulis anggota Dewan Redaksi keadilan.id, dosen dan Pengurus Harian PWI Jaya