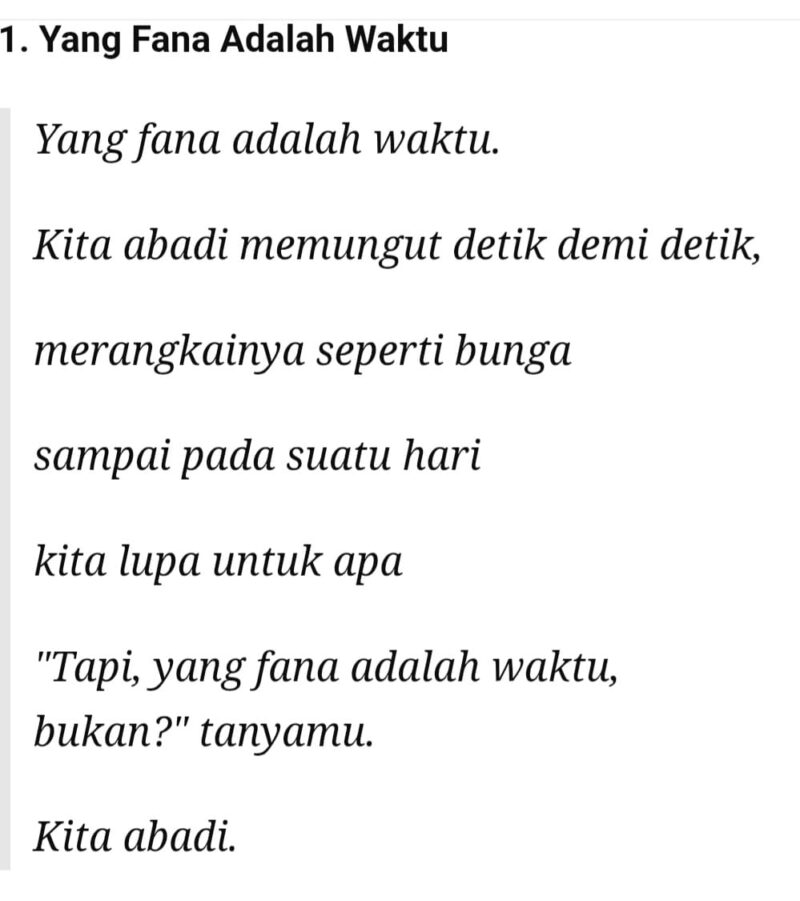BUDAYA – Puisi pernah menjadi napas peradaban. Jauh sebelum manusia mengenal kertas dan layar digital, puisi hidup dalam mantra, nyanyian, dan kisah lisan. Ia menjadi cara manusia menyimpan ingatan, menuturkan sejarah, dan memahami dunia.
Dari epos kuno seperti Gilgamesh, himne Weda di India, hingga pantun dan tembang Nusantara, puisi selalu hadir sebagai bahasa batin manusia.
Pada masa lalu, puisi bukan sekadar karya sastra. Ia adalah media pendidikan, agama, dan kebijaksanaan.
Penyair dipandang sebagai penjaga nilai dan penutur kebenaran. Di berbagai peradaban, puisi menjadi jembatan antara manusia, alam, dan keyakinan spiritual.
Memasuki era modern, fungsi puisi berubah. Ia menjadi ekspresi individual—tentang cinta, kesepian, kemarahan, dan kritik sosial.
Di Indonesia, puisi modern tumbuh melalui Pujangga Baru dan meledak pada Angkatan ’45 lewat sosok seperti Chairil Anwar. Puisi tak lagi terikat aturan kaku. Ia menjadi suara kebebasan dan kegelisahan zaman.
Namun di tengah kehidupan modern yang serba cepat, puisi perlahan tersingkir.
Dunia hari ini bergerak dalam ritme target, angka, dan efisiensi. Manusia dibentuk untuk produktif, bukan reflektif. Kecepatan dipuja, sementara kedalaman diabaikan. Ruang untuk merenung semakin sempit.
Teknologi mempercepat segalanya, tetapi juga menumpulkan rasa. Setiap hari manusia membaca ribuan kata di layar, namun sedikit yang benar-benar meresap.
Scroll menggantikan perenungan. Notifikasi menggantikan keheningan. Algoritma menentukan apa yang dilihat dan dirasakan.
Puisi tidak mati, tetapi kehilangan tempat. Ia tertimbun oleh kebisingan informasi dan budaya instan.
Padahal puisi membutuhkan jeda—sesuatu yang semakin langka dalam kehidupan modern. Puisi lahir dari kesunyian, sementara manusia modern justru takut sepi.
Ketika puisi hilang dari kehidupan sehari-hari, yang hilang bukan sekadar karya sastra. Yang ikut memudar adalah kepekaan.
Puisi adalah latihan menjadi manusia: merasakan tanpa kalkulasi, memahami tanpa tergesa, dan menyentuh makna di balik rutinitas.
Selama manusia masih memiliki rasa, puisi sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu ruang untuk kembali hidup—di tengah dunia yang terlalu sibuk untuk berhenti sejenak dan mendengar suara hatinya sendiri.