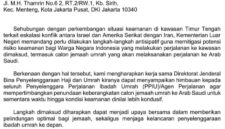Refleksi Hari Pers Nasional 2026
Oleh Bagus Sudarmanto
Krisis jurnalisme Indonesia sepanjang 2025 memperlihatkan persoalan lama yang kian menajam: tekanan bisnis dan disrupsi teknologi berjalan beriringan dengan menyempitnya ruang demokrasi. Namun ujian yang lebih menentukan justru hadir pada 2026, ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai berlaku dan berpotensi mengubah batas kerja jurnalistik ke depan.
Situasi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Secara global, kebebasan pers berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir. World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Reporters Without Borders mencatat faktor ekonomi sebagai ancaman utama kebebasan pers di berbagai negara. Lebih dari 160 dari 180 negara menghadapi rapuhnya keberlanjutan media, ditandai konsolidasi industri, penutupan redaksi, serta tekanan politik yang menggerus fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.
Indonesia berada dalam arus penurunan tersebut. Pada 2025, peringkat kebebasan pers Indonesia merosot ke posisi 127 dari 180 negara dengan skor 44,13, turun tajam dari peringkat ke-111 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan memburuknya iklim kerja jurnalistik, mulai dari kriminalisasi jurnalis, kekerasan—termasuk di ruang digital—hingga melemahnya independensi redaksi akibat tekanan ekonomi dan politik.
Memasuki 2026, tantangan kebebasan pers bergerak ke ranah yang lebih struktural. Sejak KUHP baru berlaku Januari lalu, sejumlah pasal terkait penghinaan terhadap kekuasaan, ketertiban umum, dan moralitas memunculkan kekhawatiran serius bagi kerja jurnalistik. Masalahnya bukan semata ancaman pidana, melainkan sifat pasal-pasal tersebut yang multitafsir dan berpotensi melahirkan chilling effect.
Dalam situasi seperti ini, kebebasan pers tidak lagi diuji hanya oleh kekerasan atau tekanan ekonomi, tetapi oleh ketidakpastian hukum. Ketika jurnalis memilih diam, pilihan itu sering kali bukan lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari keengganan menghadapi proses pidana yang panjang dan melelahkan. Pada titik ini, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme pembatas wacana.
Perbandingan global memperlihatkan pola yang kontras. Negara-negara dengan tradisi perlindungan pers yang kuat—seperti Norwegia, Estonia, dan Belanda—tetap berada di papan atas indeks kebebasan pers. Di Asia, Taiwan dan Korea Selatan mencatat skor jauh di atas Indonesia. Kesamaannya jelas: jaminan hukum yang tegas bagi kebebasan pers menjadi prasyarat utama, bahkan di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi. Indonesia justru melangkah ke arah sebaliknya, dengan memperluas tafsir hukum pidana terhadap ekspresi publik.
Di dalam negeri, krisis ekonomi media semakin terasa. Dewan Pers mencatat perampingan redaksi, pemutusan hubungan kerja, dan menyusutnya kapasitas liputan. Banyak media tetap terbit, tetapi fungsi jurnalistiknya mengempis. Dalam kondisi redaksi yang rapuh, keberlakuan hukum pidana yang problematik semakin memperberat posisi jurnalis, terutama jika kerja jurnalistik tidak ditempatkan secara tegas dalam kerangka perlindungan Undang-Undang Pers.
Teknologi, khususnya kecerdasan buatan, hadir sebagai faktor ambivalen. Di satu sisi, AI meningkatkan efisiensi kerja redaksi. Di sisi lain, tanpa kerangka etika dan transparansi, teknologi ini berpotensi mempercepat krisis kepercayaan publik. Karena itu, sejumlah media global menetapkan pedoman ketat: AI boleh membantu proses, tetapi keputusan editorial tetap berada di tangan manusia.
Di tengah tekanan hukum, ekonomi, dan teknologi, 2025 tidak sepenuhnya gelap. Praktik jurnalisme kolaboratif, media independen berbasis komunitas, liputan mendalam berbasis data, hingga kecenderungan slow journalism menunjukkan bahwa publik masih membutuhkan jurnalisme yang bermakna—selama ruang hukumnya tidak dipersempit.
Tiga Agenda Mendesak
Hari Pers Nasional 2026 seharusnya menjadi momentum penegasan arah. Setidaknya ada tiga agenda mendesak.
Pertama, perlindungan jurnalis dalam rezim hukum pidana baru. Pemberlakuan KUHP harus disertai jaminan bahwa kerja jurnalistik yang sah tidak dikriminalkan melalui pasal-pasal multitafsir.
Kedua, keberanian redaksional sebagai fondasi etik. Di tengah tekanan hukum dan ekonomi, jurnalisme tidak boleh sepenuhnya tunduk pada logika aman. Kritik terhadap kekuasaan dan liputan kepentingan publik tetap harus dijalankan dengan disiplin verifikasi.
Ketiga, etika teknologi untuk menjaga kepercayaan publik. Pemanfaatan AI harus transparan dan bertanggung jawab, dengan penegasan bahwa keputusan editorial berada pada manusia, bukan algoritma.
Jika 2025 adalah tahun pengakuan krisis, maka 2026 adalah tahun penentuan arah. Jurnalisme Indonesia berada di persimpangan: tunduk pada ketakutan hukum dan tekanan algoritma, atau menegaskan diri sebagai penopang akal sehat publik.
Jurnalisme tidak mati ketika redaksi ditutup. Jurnalisme mati ketika keberanian berhenti. Pada 2026, yang diuji bukan hanya masa depan pers, melainkan keberanian demokrasi itu sendiri.
Penulis adalah anggota Dewan Redaksi Keadilan.id, dosen, dan pengurus harian PWI Jaya.
PWGK Gunung Kaler Gelar Baksos Ramadan, Bantu Lansia Tunanetra di Sidoko PASTI Soroti SP3 Kasus Dugaan Diskriminasi Siswi SD di Sorong, Minta Atensi Presiden dan Kapolri Presiden Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro, Tegaskan Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Percikan Las Diduga Picu Kebakaran Pabrik Kosong di Kamal Muara Penjaringan Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Besok, Fokus 9 Pelanggaran